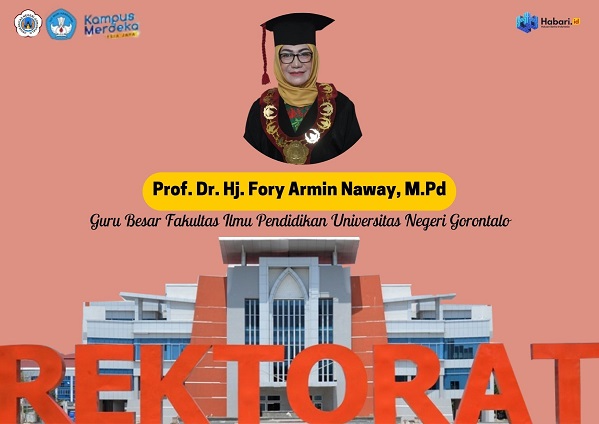Dengan begitu, sinisme masuk dalam kategori sebagai “penyakit hati” yang selalu memandang orang lain sangat tidak berarti, tidak benar dan selalu salah. Bahkan beberapa ahli psikologi berpendapat, bahwa sikap sinis atau sinisme terhadap orang lain, diidentifikasi hanya dimiliki oleh mereka yang cenderung percaya diri berlebihan, tidak mengenal dirinya secara utuh, menganggap diri yang paling baik dan paling benar, menempatkan orang lain tidak memiliki kemampuan sehingga orang lain itu dianggapnya tidak mampu dan tidak layak mendapatkan sesuatu seperti dirinya.
Dalam ranah realitas kehidupan yang sesungguhnya, sinis atau sinisme memiliki 2 dimensi yang merujuk pada dirinya sendiri dan merujuk pada orang lain. Baik sinisme terhadap diri sendiri dan orang lain tersebut, biasanya dipicu oleh ketidakmampuan seseorang mengadopsi nilai-nilai kebaikan pada dirinya sendiri dan pada orang lain. Dengan begitu, sinisme akan menghinggap dan menggejala pada seseorang yang cenderung “lupa diri” dan mengabaikan nilai-nilai positif maupun nilai-nilai kebaikan pada dirinya dan orang lain.
Sebagai sebuah penyakit yang bersumber dari ketidakjernihan berpikir, bertindak dan bersikap, maka sinisme adalah sebuah “ironi” yang sebenarnya sangat menyedihkan, bahkan tidak disadari menjadi sumber keruntuhan, kejatuhan dan sumber keterpurukan. Dalam konteks yang lebih luas lagi,, sinisme merupakan cermin dari ketidakmampuan seseorang dalam mengevaluasi diri, lupa bercermin diri, karena keterlenaannya pada kehidupan dirinya sendiri. Dalam kondisi yang demikian, maka segala kebaikan, kelebihan dan prestasi orang lain dianggapnya belum sepadan dengannya, masih dia yang tetap lebih hebat dan berprestasi. Akibatnya, segala bentuk pikiran, tindakan dan kata-katanya akan selalu “salah kaprah” dan salah sasaran, bahkan pikiran-pikiran negatif kepada dirinya dan orang lain terus saja bergelayut dalam benaknya, selalu berprasangka buruk dan menempatkan orang lain selalu salah di hadapannya.
Karena sangat terkait erat dengan aspek kejiwaan, spiritual dan moralitas, maka sinisme berpotensi disandang oleh siapapun,tanpa mengenal status sosial seseorang. Namun sinisme pada diri sendiri dan orang lain, umumnya sangat potensial akan menggejala pada 2 personal dengan status sosial yang berbeda ; yakni ; Pertama, mereka yang merasa berada pada posisi “tidak berdaya” merasa miskin misalnya, merasa tidak punya pendidikan yang memadai, merasa sebagai orang kampungan dan sebagainya. Kedua, mereka atau individu yang dikategorikan sebagai “elite” yang sudah mapan atau pernah merasakan kemapanan sebagai “orang besar”.
Jenis manusia pertama akan selalu sinis pada dirinya, jika berbicara tentang masa depan atau tentang kesuksesan. Ia mislanya akan merasa sinis, bahwa dewi fortuna tidak akan pernah berpihak kepadanya untuk masuk menjadi seorang “pilot”,karena tidak memiliki biaya dan sebagainya. Juga, mereka atau individu seperti ini, akan cenderung bersikap sinis terhadap orang lain yang status sosialnya lebih tinggi dari dirinya. Contoh ungkapan yang sering terlontar, “mana mungkin dia mau berteman dengan orang miskin seperti saya” misalnya.
Padahal, belum tentu apa yang bergelayut dalam pikirannya itu menggejala pada orang lain. Artinya, ia sama sekali tidak menghadirkan pikiran positif bahwa orang kaya juga butuh teman yang memiliki kesederhanaan misalnya. Itulah sebabnya, sinisme yang mengidap pada jenis manusia pertama ini, cenderung akan melahirkan “pesimisme akut” yang semakin membuatnya terpuruk.
Berbeda dengan jenis manusia kedua, karena ia merasa sebagai bagian dari kaum elit, “orang besar” semisal seorang pejabat atau orang kaya, maka sinisme terhadap orang lain, porsinya jauh lebih besar. Sinisme seperti ini cenderung melahirkan “keangkuhan” dan rasa percaya diri yang belebihan. Akibatnya ia akan selalu memandang orang lain tidaklah berarti apa-apa, jika dibandingkan dengan dirinya.
Bahkan, meski ia sudah mulai redup dari “panggung kehidupan” sekalipun misalnya, ia masih tetap saja bersikap sinis terhadap orang lain, terutama kepada seseorang yang dianggap sebagai rivalnya. Akibatnya lagi, hati dan pikirannya akan dipenuhi oleh aura negatif sehingga melupakan kebaikan, kelebihan dan prestasi orang lain itu dengan sangat vulgarnya.
Paling tidak, dalam konteks sinisme pada jenis personality seperti ini, umumnya melanda pada seseorang yang terserang Post Power Syndrom. Hal itu bisa terjadi, karena kurangnya penghayatan terhadap nilai-nilai kehidupan yang hakiki. Itulah sebabnya, ada yang berpendapat, bahwa sinisme “orang biasa” yang berpotensi melahirkan pesimisme itu masih bisa ditolerir dan diobati. Berbeda dengan sinisme “orang besar” yang boleh disebut sangat berbahaya dan tercela. Mengapa?, karena angkuh dan sombong itu bukan “pakaiannya” manusia, melainkan hak atau pakaiannya Sang Maha Pencipta, Penguasa alam semesta Allah SWT. Oleh karena itu, mawas diri, kemudian asupan nilai-nilai spiritual sangat urgen untuk dimanifestasikan ke dalam ruang kehidupan sehari-hari.
Sinisme yang selalu memandang diri yang paling benar, paling berprestasi, paling hebat, paling berjasa sehingga melupakan kebaikan, prestasi dan kelebihan orang lain, kesemuanya itu merupakan potret individu yang “kebablasan”, lupa diri dan kehilangan esensi kemanusiaan yang cukup parah bahkan mengerikan.
Disebut demikian, karena secara kudrati, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, sebagaimana ada siang ada malam. Dengan begitu, tidak ada alasan bagi siapapun untuk memandang dirinya yang paling hebat, paling bepengaruh dan berprestasi sehingga meremehkan orang lain. Dalam konteks ini, bahwa siapapun yang terlahir ke muka bumi, memiliki hak dan potensi yang sama untuk meraih kebaikan, menggapai sukses dan berprestasi dalam bidang masing-masing. Demikian juga, bahwa kebaikan, kesuksesan dan prestasi bukanlah monopoli orang per orang, tapi disediakan dan berpotensi untuk diraih oleh semua orang.
Yang berbeda adalah eksistensi kemanusiaan seseorang berdasarkan rentetan waktu dan masa, sebagaimana ungkapan yang mengatakan, “Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya”. Jika cahaya kehidupan mulai dirasakan meredup, maka itu adalah isyarat “cahaya nurani yang sejatinya dipertajam”, bukan sebaliknya, sibuk “memadamkan cahaya” orang lain”. Semoga.(**).